PENDUDUK, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN
Penduduk, Masyarakat dan
Kebudayaan
NAMA : ARIE APRIANDI FAJAR
NPM : 21318054
KELAS : 1TB05
JURUSAN : TEKNIK ARSITEKTUR
BAB I
PEMBAHASAN
1.1 Pertumbuhan
Penduduk
Penduduk, Masyarakat dan kebudayaan adalah tiga hal
aspek kehidupan yang saling berkaitan. Salah satunya sangat berkaitan dan tidak
dapat dipisahkan satu sama lain karena dapat saling menentukan. Penduduk
bertempat tinggal di dalam suatu wilayah tertentu dalam waktu yang tertentu
pula dan kemungkinan akan terbentuknya suatu masyarakat dari akibat perkumpulan
penduduk tersebut. Begitu pula dengan Kebudayaan yang terlahir, tumbuh dan
berkembang dalam suatu masyarakat. Menurut Selo Soemarjidan mengatakan bahwa
Masyarakat adalah Orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Jadi
hubungan antara Penduduk, Masyarakat dan Budaya merupakan hubungan yang saling
menentukan.
Dalam Sosiologi penduduk adalah perkumpulan manusia
yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk dapat
didefinisikan menjadi dua yaitu Orang yang tinggal di daerah tersebut dan Orang
yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Maksudnya dapat di
katakan penduduk suatu daerah tersebut bila memiliki surat resmi untuk tinggal
di tempat tersebut misalknya memiliki sebuah KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk
menjadi Penduduk resmi Negara Indonesia.
a.
Pertumbuhan Penduduk
Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati
wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk atau warga suatu negara atau
daerah bisa didefinisikan menjadi dua: Pertama orang yang tinggal di daerah
tersebut. Dan kedua orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut.
Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ.
Misalkan bukti kewarganegaraan sperti KTP yang digunakan sebagai identitas
WNI(Warga Negara Indonesia).
Dalam arti luas, penduduk atau populasi berarti sejumlah makhluk sejenis yang
mendiami atau menduduki tempat tertentu misalnya pohon bakau yang terdapat pada
hutan bakau, atau kera yang menempati hutan tertentu. Bahkan populasi dapat
pula dikenakan pada benda-benda sejenis yang terdapat pada suatu tempat,
misalnya kursi dalam suatu gedung sekolah. Dalam kaitannya dengan manusia, maka
pengertian penduduk adalah manusia yang mendiami dunia atau bagian-bagiannya
(Ruslan H.Prawiro, 1981 : 3).
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat
dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi
menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk
merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering
digunakan secara informal untuk sebutan nilai pertumbuhan penduduk, dan
digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia.
 |
Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah masalah ekonomi. Maksud dari masalah ekonomi ialah terbatasnya lapangan kerja yang ada di lingkungan masyarakat sekitar, diantaranya ialah meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan, anak-anak putus sekolah, serta kejahatan timbul dimana-mana. Berikut adalah data tabel jumlah penduduk dunia.
Sumber : Duran (1967), Todaro (1983), UN (2001), UN(2005)
§ Faktor
– factor Demografi
1. Fertilitas
(Kelahiran)
Kelahiran adalah istilah dalam demografi yang
mengindikasikan jumlah anak yang dilahirkan hidup, atau dalam pengertian lain
fasilitas adalah hasil produksi yang nyata dari fekunditas seorang wanita.
Berikun ini penjelasan mengenai pengukuran fertilitas:
1. Pengukuran
fasilitas tahunan adalah pengukuran kelahiran bayi pada tahun tertentu
dihubungkan dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Adapun ukuran-ukuran
fertilitas tahunan adalah:
§ Tingkat
fertilitas kasar (crude birth rate)
adalah banyaknya kelahiran hidup pada satu tahun tertentu tiap 1000 penduduk.
§ Tingkat
fertilitas umum (general fertility rate)
adalah jumlah kelahiran hidup per-1000 wanita usia reproduksi (usia 14-49 atau
14-44 tahun) pada tahun tertentu.
§ Tingkat
fertilitas menurut umur (age specific
fertility rate) adalah perhitungan tingkat fertilitas perempuan pada
tiap kelompok umur dan tahun tertentu.
§ Tingkat
ferlititas menurut ukuran urutan penduduk (birth
order specific fertility rates) adalah perhitungan fertilitas menurut
urutan kelahiran bayi oleh wanita pada umur dan tahun tertentu.
2. Pengukuran fertilitas komulatif
adalah pengukuran jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh
seorang perempuan hingga mengakhiri batas usia suburnya. Adapun
ukurannya adalah:
§ Tingkat
fertilitas total adalah jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan jumlah
tiap 1000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya dengan catatan
tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa
reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada priode
waktu tertentu.
§ Gross
reproduction rates adalah jumlah kelahiran bayi perempuan oleh 1000 perempuan
sepanjang masa reproduksinya dengan catatan tidak ada seorang perempuan yang
meninggal sebelum mengakhiri masa produksinya.
2. Mortalitas
(Kematian)
Mortalitas
atau kematian merupakan salah satu di antara tiga komponen demografi yang dapat
mempengaruhi perubahan penduduk. Informasi tentang kematian penting, tidak saja
bagi pemerintah melainkan juga bagi pihak swasta, yang terutama berkecimpung
dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Mati adalah keadaan menghilangnya semua
tanda – tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah
kelahiran hidup. Data kematian sangat diperlukan antara lain untuk proyeksi
penduduk guna perancangan pembangunan. Misalnya, perencanaan fasilitas
perumahan, fasilitas pendidikan, dan jasa – jasa lainnya untuk kepentingan
masyarakat. Data kematian juga diperlukan untuk kepentingan.
Berikut
ini adalah akibat yang muncul dari migrasi :
§ Angka kematian kasar (Crude Death Rate/CDR)
Angka
kematian kasar adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian setiap 1.000
penduduk dalam waktu satu tahun.
CDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini.
CDR = M/P x 1.000
Keterangan :
CDR = Angka kematian kasar
M = Jumlah kematian selama satu tahun
P = Jumlah penduduk pertengahan tahun
1.000 = Konstanta
Kriteria angka kematian kasar (CDR) dibedakan menjadi tiga macam.
- CDR kurang dari 10, termasuk kriteria rendah
- CDR antara 10 – 20, termasuk kriteria sedang
- CDR lebih dari 20, termasuk kriteria tinggi
CDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini.
CDR = M/P x 1.000
Keterangan :
CDR = Angka kematian kasar
M = Jumlah kematian selama satu tahun
P = Jumlah penduduk pertengahan tahun
1.000 = Konstanta
Kriteria angka kematian kasar (CDR) dibedakan menjadi tiga macam.
- CDR kurang dari 10, termasuk kriteria rendah
- CDR antara 10 – 20, termasuk kriteria sedang
- CDR lebih dari 20, termasuk kriteria tinggi
§ Angka kematian khusus (Age Specific Death Rate/ASDR)
Angka kematian khusus yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kematian setiap 1.000
penduduk pada golongan umur tertentu dalam waktu satu tahun.
ASDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini.
ASDR = Mi/Pi x 1.000
Keterangan :
ASDR = Angka kematian khusus
Mi = Jumlah kematian pada kelompok umur tertentu
Pi = Jumlah penduduk pada kelompok tertentu
1.000 = Konstanta
ASDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini.
ASDR = Mi/Pi x 1.000
Keterangan :
ASDR = Angka kematian khusus
Mi = Jumlah kematian pada kelompok umur tertentu
Pi = Jumlah penduduk pada kelompok tertentu
1.000 = Konstanta
3. Migrasi
Secara umum Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap
dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi
internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Dengan kata lain,
migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah
(negara) ke daerah (negara) lain. Ada dua dimensi penting dalam penalaahan
migrasi, yaitu dimensi ruang/daerah (spasial) dan dimensi waktu. Tinjauan
migrasi secara regional sangat penting dilakukan terutama terkait dengan
kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata.Migrasi salah satu dari
tiga komponen dasar dalam demografi, Migrasi bersama dengan dua komponen
lainnya, kelahiran dan kematian, mempengaruhi dinamika kependudukan di suatu
wilayah.
Berikut ini adalah akibat yang muncul dari migrasi :
§ Pengaruh
Kepadatan Penduduk terhadap Bidang Ekonomi
Dampak
kepadatan penduduk terhadap ekonomi adalah pendapatan per kapita berkurang
sehingga daya beli masyarakat menurun. Hal ini juga menyebabkan kemampuan
menabung masyarakat menurun sehingga dana untuk pembangunan negara berkurang.
Ak ibatnya, lapangan kerja menjadi berkurang dan pengangguran makin meningkat.
§ Pengaruh
Kepadatan Penduduk terhadap Bidang Sosial
Jika
lapangan pekerjaan berkurang, maka pengangguran akan men ingkat. Hal ini akan
meningkatkan kejahatan. Selain itu, terjadinya urbanisasi atau perpindahan
penduduk dari desa ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang layak makin
meningkatkan penduduk kota. Hal ini berdampak pada lingkungan dan kesehatan
masyarakat.
§ Pencemaran
Lingkungan
Pencemaran
atau polusi adalah penambahan segala substansi ke lingkungan akibat aktivitas
manusia.
Macam-Macam Migrasi dan Proses Migrasi
Dengan adanya wilayah yang memiliki suatu nilai
lebih maka banyak orang/ penduduk pun yang akan pergi ke wilayah itu
dikarenakan di wilayah ia tinggal sudah tidak ada lagi nilai lebihnya untuk
berkelangsungan hidupnya.
Proses migrasi pun punya cara yaitu:
§ Proses migrasi ia menetap di suatu wilayah
§ Proses migrasi hanya sementara diwilayah itu
sewaktu-waktu ia dapat
kembali
lagi ke wilayah tempat asalnya
§ Hanya sekedar berlibur diwilayah itu
Berikut
adalah macam-macam migrasi :
§ Emigrasi
adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain.
§ Imigrasi
adalah masuknya penduduk ke dalam suatu daerah negara tertentu.
§ Urbanisasi
adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota.
§ Transmigrasi
adalah perpindahan penduduk antarpulau dalam suatu Negara
§ Remigrasi
adalah kembalinya penduduk ke negara asal setelah beberapa lama berada di
negara lain.
Jenis-Jenis
Struktur Penduduk
§ Jumlah
Penduduk : Urbanisasi, Reurbanisasi, Emigrasi, Imigrasi, Remigrasi,
Transmigrasi.
§ Persebaran
Penduduk : Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk disuatu wilayah
dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per km kuadrat.
§ Komposisi
Penduduk : Merupakan sebuah mata statistik dari statistik kependudukan yang
membagi dan membahas masalah kependudukan dari segi umur dan jenis kelamin.
Bentuk
Piramida Penduduk

·
Piramida penduduk muda berbentuk limas
Piramida
ini menggambarkan jumlah penduduk usia muda lebih bedar dibanding usia dewasa.
Jumlah angka kelahiran lebih besar daripada jumlah kematoan. Contoh : India,
Brazil, Indonesia
·
Piramida penduduk stasioner atau tetap
berbentuk granat
Bentuk
ini menggambarkan jumlah penduduk usia muda seimbang dengan usia dewasa.
Tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran tidak begitu tinggi. Contoh
Negara : Swedia, Belanda, Skandinavia.
·
Piramida penduduk tua berbentuk batu nisan
Piramida
bentuk ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda lebih sedikit bila
dibandingkan dengan usia dewasa. Jika angka kelahiran jenis pria besar, maka
suatu negara bisa kekurangan penduduk. Contoh Negara : Jerman, Inggris, Belgia,
Prancis.
Rasio
Ketergantungan
Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio)
adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan
jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja)
dibandingkan dengan jumlah pendduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).
Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat
digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi
suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.
Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin
tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang
harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang
belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio
yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung
penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak
produktif lagi.
Berikut adalah rumus dari rasio ketergantungan:

b.
Masyarakat
Masyarakat
merupakan kumpulan dari penduduk yang mempunyai hubungan dan mempunyai
kepentingan untuk bersama. Menurut Koentjaraningrat masyarakat adalah kesatuan
hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu
yang bersifat kontinu,dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Dalam
arti sempit atau arti kata masyarakat berasal dari kata bahasa Arab “syaraka”
berarti ikut serta atau berpartisipasi.
Dalam
Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan melihat dari cara bermata
pencaharian. Para pakar ilmu sosial telah mengidentifikasikan masyarakat
menjadi beberapa golongan yaitu masyarakat pemburu, masyarakat pastoral
nomadis, masyarakat bercocoktanam, dan masyarakat agrikultural intensif, yang
juga disebut masyarakat peradaban. Beberapa pakar ilmu sosial juga telah
menganggap bahwa masyarakat industri dann pasca-industri sebagai kelompok yang
terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional.
Fungsi
Masyarakat :
Adapun
fungsi masyarakat bagi kehidupan manusia menurut Suhadi adalah:
a. Untuk
melindungi anggota masyarakat atau untuk menghindari segala penderitaan,
perpecahan, perselisihan dan segala bentuk kejahatan yang timbulkan oleh
individu maupun kelompok yang ada dalam masyarakat atau dari luar masyarakat
itu sendiri.
b. Untuk
menyususn kelangsungan hidup, manusia menuju tertib dan damai sesuai dengan
cita-cita warga masyarakat yang bersangkutan yang mudah bersatu dalam
mayarakat. Semakin kuat pertahanannya sehingga segala kepentingan keselamatan
serta kebutuhan hidupnya akan lebih terjamin.
c. Sistem komunikasi akan lebih lancar apabila dibandingkan
dalam bentuk individu, karena masyarakat itu dapat berbicara menggunakan
bahasa, mengetahui adat istiadat. Stabilitas pribadi akan lebih terarah dalam
bentuk positif, sehingga tujuan dari terbentuknya masyarakat itu tercapai.
1.2 Kebudayaan
dan Kepribadian
Pertumbuhan
dan Perkembangan Kebudayaan di Indonesia
·
Zaman Batu Tua
(Palaeolithikum)
Alat-alat
batu pada zaman batu tua, baik bentuk ataupun permukaan peralatan masih kasar,
misalnya kapak genggam Kapak genggam semacam itu kita kenal dari wilayah Eropa,
Afrika, Asia Tengah, sampai Punsjab(India), tapi kapak genggam semacam ini
tidak kita temukan di daerah Asia Tenggara
Berdasarkan
penelitian para ahli prehistori, bangsa-bangsa Proto-Austronesia pembawa
kebudayaan Neolithikum berupa kapak batu besar ataupun kecil bersegi-segi
berasal dari Cina Selatan, menyebar ke arah selatan, ke hilir sungai-sungai
besar sampai ke semenanjung Malaka Lalu menyebar ke Sumatera, Jawa. Kalimantan
Barat, Nusa Tenggara, sampai ke Flores, dan Sulawesi, dan berlanjut ke
Filipina.
·
Zaman Batu Muda
(Neolithikum)
Manusia
pada zaman batu muda telah mengenal dan memiliki kepandaian untuk
mencairkan/melebur logam dari biji besi dan menuangkan ke dalam cetakan dan
mendinginkannya. Oleh karena itulah mereka mampu membuat senjata untuk
mempertahankan diri dan untuk berburu serta membuat alat-alat lain yang mereka
perlukan.
Cir-ciri zaman batu muda :
1. Mulai menetap dan membuat rumah
2. Membentuk kelompok masyarakat desa
3. Bertani
4. Berternak untuk memenuhi kebutuhan hidup
1. Mulai menetap dan membuat rumah
2. Membentuk kelompok masyarakat desa
3. Bertani
4. Berternak untuk memenuhi kebutuhan hidup
Bangsa-bangsa
Proto-austronesia yang masuk dari Semenanjung Indo-China ke Indonesia itu
membawa kebudayaan Dongson, dan menyebar di Indonesia. Materi dari kebudayaan
Dongson berupa senjata-senjata tajam dan kapak berbentuk sepatu yang terbuat
dari bahan perunggu.
Kebudayaan
Hindu, Budha, dan Islam
·
Kebudayaan Hindu, Budha
Pada
abad ke-3 dan ke-4 agama hindu mulai masuk ke Indonesia di Pulau Jawa.
Perpaduan atau akulturasi antara kebudayaan setempat dengan kebudayaan. Sekitar
abad ke 5 ajaran Budha masuk ke indonesia, khususnya ke Pulau Jawa. Agama Budha
dapat dikatakan berpandangan lebih maju dibandingkan Hinduisme,sebab budhisme
tidak menghendaki adanya kasta-kasta dalam masysrakat. Walaupun demikian, kedua
agama itu di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa tumbuh dan berdampingan secara
damai. Baik penganut hinduisme maupun budhisme masng-masing menghasilkan karya-
karya budaya yang bernilai tinggi dalam seni bangunan, arsitektur, seni pahat,
seni ukir, maupun seni sastra, seperti tercermin dalam bangunan, relief yang
diabadikan dalam candi-candi di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur diantaranya
yaitu Borobudur, Mendut, Prambanan, Kalasan, Badut, Kidal, Jago, Singosari, dll.
·
Kebudayaan Islam
Abad
ke 15 da 16 agama islam telah dikembangkan di Indonesia, oleh para
pemuka-pemuka islam yang disebut Walisongo. Titik penyebaran agama Islam pada
abad itu terletak di Pulau Jawa. Sebenarnya agama Islam masuk ke Indonesia,
khususnya di Pulau Jawa sebelum abad ke 11 sudah ada wanita islam yang
meninggal dan dimakamkan di Kota Gresik. Masuknya agama Islam ke Indonesia
berlangsung secara damai. Hal ini di karena masuknya Islam ke Indonesia tidak
secara paksa.
Abad
ke 15 ketika kejayaan maritim Majapahit mulai surut , berkembanglah
negara-negara pantai yang dapat merongrong kekuasaan dan kewibawaan majapahit
yang berpusat pemerintahan di pedalaman. Negara- negara yang dimaksud adalah
Negara malaka di Semenanjung Malaka,Negara Aceh di ujung Sumatera, Negara
Banten di Jawa Barat, Negara Demak di Pesisir Utara Jawa Tengah, Negara Goa di
Sulawesi Selatan . Dalam proses perkembangan negara-negara tersebut yang
dikendalikan oleh pedagang. Pedagang kaya dan golongan bangsawan kota- kota
pelabuhan, nampaknya telah terpengaruh dan menganut agama Islam. Daerah-daerah
yang belum tepengaruh oleh kebudayaan Hindu, agama Islam mempunyai pengaruh
yang mendalam dalam kehidupan penduduk. Di daerah yang bersangkutan. Misalnya
Aceh, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Timur, Sumatera Barat, dan Pesisr
Kalimantan.
1.3 Kebudayaan
Barat
Unsur kebudayaan barat juga memberi warna terhadap corak lain dari
kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia adalah kebudayaan Barat. Masuknya
budaya Barat ke Negara Republik Indonesia ketika kaum kolonialis atau penjajah
masuk ke Indonesia, terutama bangsa Belanda. Penguasaan dan kekuasaan
perusahaan dagang Belanda (VOC) dan berlanjut dengan pemerintahan kolonialis
Belanda, di kota-kota propinsi, kabupaten muncul bangunan-bangunan dengan
bergaya arsitektur Barat. Dalam waktu yang sama, dikota-kota pusat
pemarintahan, terutama di Jawa, Sulawesi Utara, dan Maluku berkembang dua
lapisan sosial ; Lapisan sosial yang terdiri dari kaum buruh, dan kaum pegawai.
Sehubungan dengan itu penjelasan UUD’45 memberikan rumusan tentang
kebudayaan memberikan rumusan tentang kebudayaaan bangsa Indonesia adalah:
kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya,
termasuk kebudayaan lama dan asli yang ada sebagai puncak kebudayaan di
daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dalam penjelasan UUD’45 ditujukan ke arah
mana kebudayaan itu diarahkan, yaitu menuju kearah kemajuan budaya dan
persatuan, dengan tidak menolak bahan baru kebudayaan asing yang dapat
mengembangkan kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan
bangsa Indonesia.
BAB II
PENUTUP
KESIMPULAN
Individu
adalah kesatuan utuh antara jasmani dan rohani. Setiap individu mempunyai ciri
khas dan kebutuhan yang tersendiri. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut,setipa
individu membutuhkan individu lain. Karena itulah individu selalu hidup
berkelompok membentuk masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah orang yang
hidup dalam suatu daerah saling berhubungan dan terikat satu sama lain sehingga
memiliki rasa solidaritas dan menghasilkan kebudayaan. Setiap individu
dalam masyarakat mempunyai peran dan kedudukan yang berbeda. Setiap individu
diharapkan dapat berperan sesuai dengan kedudukannya sehingga tercipta
ketertiban, kenyamanan, kesetabilan hidup bermasyarakat, yang akhirnya tujuan
bersama dapat tercapai.
SARAN
Untuk menghindari masalah kepadatan penduduk pemerintah harus lebih
disiplin lagi dalam mengkaji peraturan-peraturan yang telah di tetapkan dan
sebagai warga negara juga perlu menyadari dan menjalankan akan pentingnya
aturan tersebut.
Kebudayaan yang telah diwariskan oleh zaman terdahulu wajib kita jaga
dan lestarikan. Selain berfungsi untuk keistimewaan dan keunikan negara juga
akan berfungsi untuk generasi-generasi berikutnya seperti anak dan cucu kita
nanti.
DAFTAR PUSTAKA
H. Abu Ahmadi, Drs, ILMU SOSIAL DASAR, Rineka
Cipta, 1990
H. Hartomo, Drs dan Arnicun Aziz, Dra, MKDU
ISD, Bumi Aksara,
Desember, 1990
Mawardi, Drs – Nurs Hidayati, Ir, 2009, ILMU
ALAMIAH DASAR, ILMU SOSIAL DASAR, ILMU BUDAYA DASAR, Bandung: Pustaka Setia.
Munandar Soelaeman, ISD TEORI DAN KONSEP ILMU
SOSIAL, edisi
revisi, PT. Eresco Bandung, 1989
Soewaryo Wangsanegara, BUKU MATERI POKOK ISD,
(modul 1-3),
Penerbit Karunika, Jakarta
Penduduk, Masyarakat dan
Kebudayaan
NAMA : ARIE APRIANDI FAJAR
NPM : 21318054
KELAS : 1TB05
JURUSAN : TEKNIK ARSITEKTUR
BAB I
PEMBAHASAN
1.1 Pertumbuhan
Penduduk
Penduduk, Masyarakat dan kebudayaan adalah tiga hal
aspek kehidupan yang saling berkaitan. Salah satunya sangat berkaitan dan tidak
dapat dipisahkan satu sama lain karena dapat saling menentukan. Penduduk
bertempat tinggal di dalam suatu wilayah tertentu dalam waktu yang tertentu
pula dan kemungkinan akan terbentuknya suatu masyarakat dari akibat perkumpulan
penduduk tersebut. Begitu pula dengan Kebudayaan yang terlahir, tumbuh dan
berkembang dalam suatu masyarakat. Menurut Selo Soemarjidan mengatakan bahwa
Masyarakat adalah Orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Jadi
hubungan antara Penduduk, Masyarakat dan Budaya merupakan hubungan yang saling
menentukan.
Dalam Sosiologi penduduk adalah perkumpulan manusia
yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk dapat
didefinisikan menjadi dua yaitu Orang yang tinggal di daerah tersebut dan Orang
yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Maksudnya dapat di
katakan penduduk suatu daerah tersebut bila memiliki surat resmi untuk tinggal
di tempat tersebut misalknya memiliki sebuah KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk
menjadi Penduduk resmi Negara Indonesia.
a.
Pertumbuhan Penduduk
Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati
wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk atau warga suatu negara atau
daerah bisa didefinisikan menjadi dua: Pertama orang yang tinggal di daerah
tersebut. Dan kedua orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut.
Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ.
Misalkan bukti kewarganegaraan sperti KTP yang digunakan sebagai identitas
WNI(Warga Negara Indonesia).
Dalam arti luas, penduduk atau populasi berarti sejumlah makhluk sejenis yang
mendiami atau menduduki tempat tertentu misalnya pohon bakau yang terdapat pada
hutan bakau, atau kera yang menempati hutan tertentu. Bahkan populasi dapat
pula dikenakan pada benda-benda sejenis yang terdapat pada suatu tempat,
misalnya kursi dalam suatu gedung sekolah. Dalam kaitannya dengan manusia, maka
pengertian penduduk adalah manusia yang mendiami dunia atau bagian-bagiannya
(Ruslan H.Prawiro, 1981 : 3).
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat
dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi
menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk
merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering
digunakan secara informal untuk sebutan nilai pertumbuhan penduduk, dan
digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia.
 |
Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah masalah ekonomi. Maksud dari masalah ekonomi ialah terbatasnya lapangan kerja yang ada di lingkungan masyarakat sekitar, diantaranya ialah meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan, anak-anak putus sekolah, serta kejahatan timbul dimana-mana. Berikut adalah data tabel jumlah penduduk dunia.
Sumber : Duran (1967), Todaro (1983), UN (2001), UN(2005)
§ Faktor
– factor Demografi
1. Fertilitas
(Kelahiran)
Kelahiran adalah istilah dalam demografi yang
mengindikasikan jumlah anak yang dilahirkan hidup, atau dalam pengertian lain
fasilitas adalah hasil produksi yang nyata dari fekunditas seorang wanita.
Berikun ini penjelasan mengenai pengukuran fertilitas:
1. Pengukuran
fasilitas tahunan adalah pengukuran kelahiran bayi pada tahun tertentu
dihubungkan dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Adapun ukuran-ukuran
fertilitas tahunan adalah:
§ Tingkat
fertilitas kasar (crude birth rate)
adalah banyaknya kelahiran hidup pada satu tahun tertentu tiap 1000 penduduk.
§ Tingkat
fertilitas umum (general fertility rate)
adalah jumlah kelahiran hidup per-1000 wanita usia reproduksi (usia 14-49 atau
14-44 tahun) pada tahun tertentu.
§ Tingkat
fertilitas menurut umur (age specific
fertility rate) adalah perhitungan tingkat fertilitas perempuan pada
tiap kelompok umur dan tahun tertentu.
§ Tingkat
ferlititas menurut ukuran urutan penduduk (birth
order specific fertility rates) adalah perhitungan fertilitas menurut
urutan kelahiran bayi oleh wanita pada umur dan tahun tertentu.
2. Pengukuran fertilitas komulatif
adalah pengukuran jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh
seorang perempuan hingga mengakhiri batas usia suburnya. Adapun
ukurannya adalah:
§ Tingkat
fertilitas total adalah jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan jumlah
tiap 1000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya dengan catatan
tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa
reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada priode
waktu tertentu.
§ Gross
reproduction rates adalah jumlah kelahiran bayi perempuan oleh 1000 perempuan
sepanjang masa reproduksinya dengan catatan tidak ada seorang perempuan yang
meninggal sebelum mengakhiri masa produksinya.
2. Mortalitas
(Kematian)
Mortalitas
atau kematian merupakan salah satu di antara tiga komponen demografi yang dapat
mempengaruhi perubahan penduduk. Informasi tentang kematian penting, tidak saja
bagi pemerintah melainkan juga bagi pihak swasta, yang terutama berkecimpung
dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Mati adalah keadaan menghilangnya semua
tanda – tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah
kelahiran hidup. Data kematian sangat diperlukan antara lain untuk proyeksi
penduduk guna perancangan pembangunan. Misalnya, perencanaan fasilitas
perumahan, fasilitas pendidikan, dan jasa – jasa lainnya untuk kepentingan
masyarakat. Data kematian juga diperlukan untuk kepentingan.
Berikut
ini adalah akibat yang muncul dari migrasi :
§ Angka kematian kasar (Crude Death Rate/CDR)
Angka
kematian kasar adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian setiap 1.000
penduduk dalam waktu satu tahun.
CDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini.
CDR = M/P x 1.000
Keterangan :
CDR = Angka kematian kasar
M = Jumlah kematian selama satu tahun
P = Jumlah penduduk pertengahan tahun
1.000 = Konstanta
Kriteria angka kematian kasar (CDR) dibedakan menjadi tiga macam.
- CDR kurang dari 10, termasuk kriteria rendah
- CDR antara 10 – 20, termasuk kriteria sedang
- CDR lebih dari 20, termasuk kriteria tinggi
CDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini.
CDR = M/P x 1.000
Keterangan :
CDR = Angka kematian kasar
M = Jumlah kematian selama satu tahun
P = Jumlah penduduk pertengahan tahun
1.000 = Konstanta
Kriteria angka kematian kasar (CDR) dibedakan menjadi tiga macam.
- CDR kurang dari 10, termasuk kriteria rendah
- CDR antara 10 – 20, termasuk kriteria sedang
- CDR lebih dari 20, termasuk kriteria tinggi
§ Angka kematian khusus (Age Specific Death Rate/ASDR)
Angka kematian khusus yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kematian setiap 1.000
penduduk pada golongan umur tertentu dalam waktu satu tahun.
ASDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini.
ASDR = Mi/Pi x 1.000
Keterangan :
ASDR = Angka kematian khusus
Mi = Jumlah kematian pada kelompok umur tertentu
Pi = Jumlah penduduk pada kelompok tertentu
1.000 = Konstanta
ASDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini.
ASDR = Mi/Pi x 1.000
Keterangan :
ASDR = Angka kematian khusus
Mi = Jumlah kematian pada kelompok umur tertentu
Pi = Jumlah penduduk pada kelompok tertentu
1.000 = Konstanta
3. Migrasi
Secara umum Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap
dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi
internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Dengan kata lain,
migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah
(negara) ke daerah (negara) lain. Ada dua dimensi penting dalam penalaahan
migrasi, yaitu dimensi ruang/daerah (spasial) dan dimensi waktu. Tinjauan
migrasi secara regional sangat penting dilakukan terutama terkait dengan
kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata.Migrasi salah satu dari
tiga komponen dasar dalam demografi, Migrasi bersama dengan dua komponen
lainnya, kelahiran dan kematian, mempengaruhi dinamika kependudukan di suatu
wilayah.
Berikut ini adalah akibat yang muncul dari migrasi :
§ Pengaruh
Kepadatan Penduduk terhadap Bidang Ekonomi
Dampak
kepadatan penduduk terhadap ekonomi adalah pendapatan per kapita berkurang
sehingga daya beli masyarakat menurun. Hal ini juga menyebabkan kemampuan
menabung masyarakat menurun sehingga dana untuk pembangunan negara berkurang.
Ak ibatnya, lapangan kerja menjadi berkurang dan pengangguran makin meningkat.
§ Pengaruh
Kepadatan Penduduk terhadap Bidang Sosial
Jika
lapangan pekerjaan berkurang, maka pengangguran akan men ingkat. Hal ini akan
meningkatkan kejahatan. Selain itu, terjadinya urbanisasi atau perpindahan
penduduk dari desa ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang layak makin
meningkatkan penduduk kota. Hal ini berdampak pada lingkungan dan kesehatan
masyarakat.
§ Pencemaran
Lingkungan
Pencemaran
atau polusi adalah penambahan segala substansi ke lingkungan akibat aktivitas
manusia.
Macam-Macam Migrasi dan Proses Migrasi
Dengan adanya wilayah yang memiliki suatu nilai
lebih maka banyak orang/ penduduk pun yang akan pergi ke wilayah itu
dikarenakan di wilayah ia tinggal sudah tidak ada lagi nilai lebihnya untuk
berkelangsungan hidupnya.
Proses migrasi pun punya cara yaitu:
§ Proses migrasi ia menetap di suatu wilayah
§ Proses migrasi hanya sementara diwilayah itu
sewaktu-waktu ia dapat
kembali
lagi ke wilayah tempat asalnya
§ Hanya sekedar berlibur diwilayah itu
Berikut
adalah macam-macam migrasi :
§ Emigrasi
adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain.
§ Imigrasi
adalah masuknya penduduk ke dalam suatu daerah negara tertentu.
§ Urbanisasi
adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota.
§ Transmigrasi
adalah perpindahan penduduk antarpulau dalam suatu Negara
§ Remigrasi
adalah kembalinya penduduk ke negara asal setelah beberapa lama berada di
negara lain.
Jenis-Jenis
Struktur Penduduk
§ Jumlah
Penduduk : Urbanisasi, Reurbanisasi, Emigrasi, Imigrasi, Remigrasi,
Transmigrasi.
§ Persebaran
Penduduk : Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk disuatu wilayah
dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per km kuadrat.
§ Komposisi
Penduduk : Merupakan sebuah mata statistik dari statistik kependudukan yang
membagi dan membahas masalah kependudukan dari segi umur dan jenis kelamin.
Bentuk
Piramida Penduduk

·
Piramida penduduk muda berbentuk limas
Piramida
ini menggambarkan jumlah penduduk usia muda lebih bedar dibanding usia dewasa.
Jumlah angka kelahiran lebih besar daripada jumlah kematoan. Contoh : India,
Brazil, Indonesia
·
Piramida penduduk stasioner atau tetap
berbentuk granat
Bentuk
ini menggambarkan jumlah penduduk usia muda seimbang dengan usia dewasa.
Tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran tidak begitu tinggi. Contoh
Negara : Swedia, Belanda, Skandinavia.
·
Piramida penduduk tua berbentuk batu nisan
Piramida
bentuk ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda lebih sedikit bila
dibandingkan dengan usia dewasa. Jika angka kelahiran jenis pria besar, maka
suatu negara bisa kekurangan penduduk. Contoh Negara : Jerman, Inggris, Belgia,
Prancis.
Rasio
Ketergantungan
Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio)
adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan
jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja)
dibandingkan dengan jumlah pendduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).
Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat
digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi
suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.
Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin
tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang
harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang
belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio
yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung
penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak
produktif lagi.
Berikut adalah rumus dari rasio ketergantungan:

b.
Masyarakat
Masyarakat
merupakan kumpulan dari penduduk yang mempunyai hubungan dan mempunyai
kepentingan untuk bersama. Menurut Koentjaraningrat masyarakat adalah kesatuan
hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu
yang bersifat kontinu,dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Dalam
arti sempit atau arti kata masyarakat berasal dari kata bahasa Arab “syaraka”
berarti ikut serta atau berpartisipasi.
Dalam
Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan melihat dari cara bermata
pencaharian. Para pakar ilmu sosial telah mengidentifikasikan masyarakat
menjadi beberapa golongan yaitu masyarakat pemburu, masyarakat pastoral
nomadis, masyarakat bercocoktanam, dan masyarakat agrikultural intensif, yang
juga disebut masyarakat peradaban. Beberapa pakar ilmu sosial juga telah
menganggap bahwa masyarakat industri dann pasca-industri sebagai kelompok yang
terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional.
Fungsi
Masyarakat :
Adapun
fungsi masyarakat bagi kehidupan manusia menurut Suhadi adalah:
a. Untuk
melindungi anggota masyarakat atau untuk menghindari segala penderitaan,
perpecahan, perselisihan dan segala bentuk kejahatan yang timbulkan oleh
individu maupun kelompok yang ada dalam masyarakat atau dari luar masyarakat
itu sendiri.
b. Untuk
menyususn kelangsungan hidup, manusia menuju tertib dan damai sesuai dengan
cita-cita warga masyarakat yang bersangkutan yang mudah bersatu dalam
mayarakat. Semakin kuat pertahanannya sehingga segala kepentingan keselamatan
serta kebutuhan hidupnya akan lebih terjamin.
c. Sistem komunikasi akan lebih lancar apabila dibandingkan
dalam bentuk individu, karena masyarakat itu dapat berbicara menggunakan
bahasa, mengetahui adat istiadat. Stabilitas pribadi akan lebih terarah dalam
bentuk positif, sehingga tujuan dari terbentuknya masyarakat itu tercapai.
1.2 Kebudayaan
dan Kepribadian
Pertumbuhan
dan Perkembangan Kebudayaan di Indonesia
·
Zaman Batu Tua
(Palaeolithikum)
Alat-alat
batu pada zaman batu tua, baik bentuk ataupun permukaan peralatan masih kasar,
misalnya kapak genggam Kapak genggam semacam itu kita kenal dari wilayah Eropa,
Afrika, Asia Tengah, sampai Punsjab(India), tapi kapak genggam semacam ini
tidak kita temukan di daerah Asia Tenggara
Berdasarkan
penelitian para ahli prehistori, bangsa-bangsa Proto-Austronesia pembawa
kebudayaan Neolithikum berupa kapak batu besar ataupun kecil bersegi-segi
berasal dari Cina Selatan, menyebar ke arah selatan, ke hilir sungai-sungai
besar sampai ke semenanjung Malaka Lalu menyebar ke Sumatera, Jawa. Kalimantan
Barat, Nusa Tenggara, sampai ke Flores, dan Sulawesi, dan berlanjut ke
Filipina.
·
Zaman Batu Muda
(Neolithikum)
Manusia
pada zaman batu muda telah mengenal dan memiliki kepandaian untuk
mencairkan/melebur logam dari biji besi dan menuangkan ke dalam cetakan dan
mendinginkannya. Oleh karena itulah mereka mampu membuat senjata untuk
mempertahankan diri dan untuk berburu serta membuat alat-alat lain yang mereka
perlukan.
Cir-ciri zaman batu muda :
1. Mulai menetap dan membuat rumah
2. Membentuk kelompok masyarakat desa
3. Bertani
4. Berternak untuk memenuhi kebutuhan hidup
1. Mulai menetap dan membuat rumah
2. Membentuk kelompok masyarakat desa
3. Bertani
4. Berternak untuk memenuhi kebutuhan hidup
Bangsa-bangsa
Proto-austronesia yang masuk dari Semenanjung Indo-China ke Indonesia itu
membawa kebudayaan Dongson, dan menyebar di Indonesia. Materi dari kebudayaan
Dongson berupa senjata-senjata tajam dan kapak berbentuk sepatu yang terbuat
dari bahan perunggu.
Kebudayaan
Hindu, Budha, dan Islam
·
Kebudayaan Hindu, Budha
Pada
abad ke-3 dan ke-4 agama hindu mulai masuk ke Indonesia di Pulau Jawa.
Perpaduan atau akulturasi antara kebudayaan setempat dengan kebudayaan. Sekitar
abad ke 5 ajaran Budha masuk ke indonesia, khususnya ke Pulau Jawa. Agama Budha
dapat dikatakan berpandangan lebih maju dibandingkan Hinduisme,sebab budhisme
tidak menghendaki adanya kasta-kasta dalam masysrakat. Walaupun demikian, kedua
agama itu di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa tumbuh dan berdampingan secara
damai. Baik penganut hinduisme maupun budhisme masng-masing menghasilkan karya-
karya budaya yang bernilai tinggi dalam seni bangunan, arsitektur, seni pahat,
seni ukir, maupun seni sastra, seperti tercermin dalam bangunan, relief yang
diabadikan dalam candi-candi di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur diantaranya
yaitu Borobudur, Mendut, Prambanan, Kalasan, Badut, Kidal, Jago, Singosari, dll.
·
Kebudayaan Islam
Abad
ke 15 da 16 agama islam telah dikembangkan di Indonesia, oleh para
pemuka-pemuka islam yang disebut Walisongo. Titik penyebaran agama Islam pada
abad itu terletak di Pulau Jawa. Sebenarnya agama Islam masuk ke Indonesia,
khususnya di Pulau Jawa sebelum abad ke 11 sudah ada wanita islam yang
meninggal dan dimakamkan di Kota Gresik. Masuknya agama Islam ke Indonesia
berlangsung secara damai. Hal ini di karena masuknya Islam ke Indonesia tidak
secara paksa.
Abad
ke 15 ketika kejayaan maritim Majapahit mulai surut , berkembanglah
negara-negara pantai yang dapat merongrong kekuasaan dan kewibawaan majapahit
yang berpusat pemerintahan di pedalaman. Negara- negara yang dimaksud adalah
Negara malaka di Semenanjung Malaka,Negara Aceh di ujung Sumatera, Negara
Banten di Jawa Barat, Negara Demak di Pesisir Utara Jawa Tengah, Negara Goa di
Sulawesi Selatan . Dalam proses perkembangan negara-negara tersebut yang
dikendalikan oleh pedagang. Pedagang kaya dan golongan bangsawan kota- kota
pelabuhan, nampaknya telah terpengaruh dan menganut agama Islam. Daerah-daerah
yang belum tepengaruh oleh kebudayaan Hindu, agama Islam mempunyai pengaruh
yang mendalam dalam kehidupan penduduk. Di daerah yang bersangkutan. Misalnya
Aceh, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Timur, Sumatera Barat, dan Pesisr
Kalimantan.
1.3 Kebudayaan
Barat
Unsur kebudayaan barat juga memberi warna terhadap corak lain dari
kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia adalah kebudayaan Barat. Masuknya
budaya Barat ke Negara Republik Indonesia ketika kaum kolonialis atau penjajah
masuk ke Indonesia, terutama bangsa Belanda. Penguasaan dan kekuasaan
perusahaan dagang Belanda (VOC) dan berlanjut dengan pemerintahan kolonialis
Belanda, di kota-kota propinsi, kabupaten muncul bangunan-bangunan dengan
bergaya arsitektur Barat. Dalam waktu yang sama, dikota-kota pusat
pemarintahan, terutama di Jawa, Sulawesi Utara, dan Maluku berkembang dua
lapisan sosial ; Lapisan sosial yang terdiri dari kaum buruh, dan kaum pegawai.
Sehubungan dengan itu penjelasan UUD’45 memberikan rumusan tentang
kebudayaan memberikan rumusan tentang kebudayaaan bangsa Indonesia adalah:
kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya,
termasuk kebudayaan lama dan asli yang ada sebagai puncak kebudayaan di
daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dalam penjelasan UUD’45 ditujukan ke arah
mana kebudayaan itu diarahkan, yaitu menuju kearah kemajuan budaya dan
persatuan, dengan tidak menolak bahan baru kebudayaan asing yang dapat
mengembangkan kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan
bangsa Indonesia.
BAB II
PENUTUP
KESIMPULAN
Individu
adalah kesatuan utuh antara jasmani dan rohani. Setiap individu mempunyai ciri
khas dan kebutuhan yang tersendiri. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut,setipa
individu membutuhkan individu lain. Karena itulah individu selalu hidup
berkelompok membentuk masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah orang yang
hidup dalam suatu daerah saling berhubungan dan terikat satu sama lain sehingga
memiliki rasa solidaritas dan menghasilkan kebudayaan. Setiap individu
dalam masyarakat mempunyai peran dan kedudukan yang berbeda. Setiap individu
diharapkan dapat berperan sesuai dengan kedudukannya sehingga tercipta
ketertiban, kenyamanan, kesetabilan hidup bermasyarakat, yang akhirnya tujuan
bersama dapat tercapai.
SARAN
Untuk menghindari masalah kepadatan penduduk pemerintah harus lebih
disiplin lagi dalam mengkaji peraturan-peraturan yang telah di tetapkan dan
sebagai warga negara juga perlu menyadari dan menjalankan akan pentingnya
aturan tersebut.
Kebudayaan yang telah diwariskan oleh zaman terdahulu wajib kita jaga
dan lestarikan. Selain berfungsi untuk keistimewaan dan keunikan negara juga
akan berfungsi untuk generasi-generasi berikutnya seperti anak dan cucu kita
nanti.
DAFTAR PUSTAKA
H. Abu Ahmadi, Drs, ILMU SOSIAL DASAR, Rineka
Cipta, 1990
H. Hartomo, Drs dan Arnicun Aziz, Dra, MKDU
ISD, Bumi Aksara,
Desember, 1990
Mawardi, Drs – Nurs Hidayati, Ir, 2009, ILMU
ALAMIAH DASAR, ILMU SOSIAL DASAR, ILMU BUDAYA DASAR, Bandung: Pustaka Setia.
Munandar Soelaeman, ISD TEORI DAN KONSEP ILMU
SOSIAL, edisi
revisi, PT. Eresco Bandung, 1989
Soewaryo Wangsanegara, BUKU MATERI POKOK ISD,
(modul 1-3),
Penerbit Karunika, Jakarta

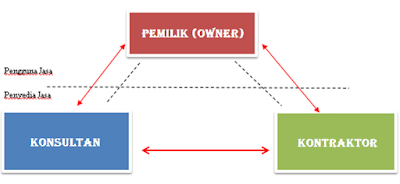

Komentar
Posting Komentar